“Gandrung yang memiliki makna Cinta, begitu pentingnya bagi masyarakat Banyuwangi. Sehingga wajarlah jika Seni Gandrung menjadi ikon wisata budaya dan identitas bersama bagi Banyuwangi. Lebih menarik lagi di era Bupati Ir. H Samsul Hadi, -melalui Surat Keputusannya tertanggal 31 Desember 2002-, akhirnya Gandrung secara resmi dijadikan Maskotnya Kabupaten Banyuwangi. Berikut sejarah dan makna filosofi di balik eksistensi Gandrung Banyuwangi.”
Dalam literasi yang ada bahwasanya sekitar tahun 1850 an, ada sebuah Sanggar Tari ternama kala itu. Sanggar Tari tersebut didirikan oleh Midin dari Semarang dan menikahi Raminah di Cungking Banyuwangi, mempunyai murid laki-laki bernama Marsan warga Cungking. Namun pasangan Midin dan Raminah hanya melahirkan keturunan anak-anak perempuan. Sejak itulah penari Gandrung yang semula dilakukan kalangan laki-laki diteruskan kalangan perempuan.
Menurut catatan buku karya John Scholt berjudul “Gandroeng Van Banjoewangi” yang terbit pada tahun 1927, mengungkapkan tentang Kesenian Gandrung. Buku tersebut menjelaskan bahwa pada tahun 1895 telah lahir Gandrung perempuan pertama bernama “Semi”. Pentas Kesenian Gandrung saat itu banyak mengisi acara-acara penting baik yang diadakan masyarakat berada maupun oleh kolonial Belanda.
Seiring perjalanan waktu, tata busana yang dikenakan penari Gandrung terbilang khas. Yakni menunjukkan bahwa busananya sangat berbeda dengan tata busana bagian Jawa. Hal ini karena masih terdapat pengaruh Bali yang muncul, yaitu dari pengaruh Kerajaan Blambangan kala itu.
Sebagaimana yang selalu tampak, busana pada bagian tubuh para penari Gandrung adalah baju dari bahan beludru hitam. Selanjutnya melekat ornamen kuning emas sebagai hiasan. Selain itu, ada manik-manik yang mengkilat dengan bentuk menyerupai leher botol, melilit leher sampai ke dada. Sementara pada bagian pundak, dan setengah punggungnya tampak terbuka. Meskipun tidaklah menganga lebar.
Adapun yang menempel pada bagian leher, baju busana penari terdapat ilat-ilatan samppai menutup dada. Fungsinya adalah sebagai penghias bagian atas. Sedangkan bagian lengan tampak hiasan masing-masing kelat bahu satu buah, serta pada bagian pinggang terdapat ikat pinggang dan sembong kain berwarna-warni untuk hiasan. Seluruh bagian hiasan tersebut juga dilengkapi selendang pada bagian bahu dengan warna yang khas sebagai pilihannya.

Adapun Omprog atau mahkota penari Gandrung, memiliki ornamen dan hiasan khas. Dimana omprognya berbahan kulit kerbau yang sudah dibersihkan berhiaskan ornamen emas dan merah. Juga terdapat ornamen Putra Bima, seorang tokoh Antasena yang mempunyai kepala raksasa tetapi badannya berbentuk ular naga yang menutup semua bagian rambut para penari Gandrung Banyuwangi.
Sesuai literasi bahwasanya ornamen Antasena di masa lalu tidak melekat pada bagian mahkota. Akan tapi setengah terlepas mirip sayap burung. Lalu pada tahun 1960-an, ornamen ekor Antasena tersebut akhirnya terlekat pada bagian omprog sampai sekarang dilestarikan.
Yang menarik, sering berjalannya waktu membuat mahkota tersebut mempunyai ornamen tambahan berupa perak. Fungsinya untuk memberi kesaan bulat telur pada bagian wajah sang penari. Selain itu juga terdapat tambahan ornamen bunga pada bagian atasnya, namanya Cundhuk Mentul. Bahkan di bagian omprog tersebut juga dipasang hio untuk menciptakan kesan magis yang mendalam.
Sedangkan karakteristik penari gandrung senantiasa menggunakan kain batik dengan corak bervariasi. Namun corak yang paling populer dan sangat khas yaitu batik bercorak gajah oling, lalu corak tumbuh-tumbuhan berserta aksen belalai gajah pada dasar kain putih sebagai ciri khas batik asli Banyuwangi Jawa Timur.
Dalam sejarahnya, jauh sebelum tahun 1930 an, para penari Gandrung tidak pernah menggunakan kaus kaki. Akan tetapi setelah tahun 1930 tersebut, para penari selalu memakai kaus kaki berwarna putih pada tiap pertunjukan. Di masa lalu, penarii Gandrung selalu menyertakan properti tambahan seperti dua buah kipas dalam pertunjukan. Akan tetapi saat ini, penari Gandrung hanya menggunakan satu buah kipas untuk bagian-bagian tertentu, terutama pada bagian pertunjukan seblang subuh sebagai pertunjukan penutupnya.
Menyangkut ciri-ciri khas musik pengiringnya, kesenian Gandrung Banyuwangi setiap tampil tak dapat dipisahkan dengan adanya satu buah gong atau kempul, satu buah triangle atau kluncing, satu atau dua buah biola, sepasang kethuk, juga dua buah kendhang. Ada kalamya saat pertunjukan diselingi saron Bali, rebana, angklung untuk bentuk kreas disertai electone sebagai variasinya.
Agar pertunjukan kesenian Gandrung lebih menarik dan meriah, biasanya juga dengan iringan panjak atau pemberi semangat. Tujuannya adalah untuk mengundang, memberi semangat, atau menambahkan efek lucu pada tiap gerak tarian gandrung. Pemain kluncing juga bisa mengambil peran panjak atau yang lainnya. ***




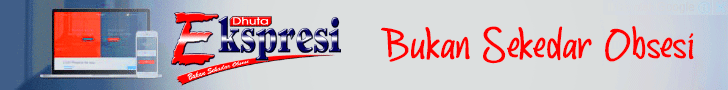






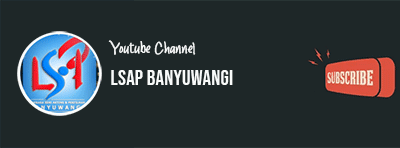
Makna Filosofi Tarian Gandrung merupakan perpaduan antara ungkapan rasa syukur para petani atas hasil panen yang melimpah, dan juga sebagai identitas budaya masyarakat Banyuwangi, serta dapat dimaknai sebagai suatu perjuangan. Secara harfiah, “gandrung” berarti ‘tergila-gila’ atau ‘jatuh cinta’, yang mencerminkan rasa cinta masyarakat Banyuwangi terhadap alam, budaya, dan tanah air. Tarian Gandrung ini juga mengandung nilai kepahlawanan, kebersamaan, dan keharmonisan antara manusia, alam, serta spiritualitas. BRAVO DHUTA EKSPRESI DAN LSAP BANYUWANGI “JAYA JAYA JAYA”